Siksaan Di Ujung Usia
Ia hanya terbaring lemah tak berdaya. Tubuhnya tak bertenaga lagi. Tak sejaya dulu saat berusia 30an. Kini wajah cantiknya yang selalu terpoles sepabrik bedak kosmetik itu mulai keriput. Rambutnya yang dulu setiap minggu selalu perawatan ke salon kecantikan. Kini telah memutih karena uban. Sepanjang hari ia merintih di atas ranjang reot yang sudah termakan usia itu. Sama seperti dirinya yang telah berusia senja. Namun naas, kebahagiaan tak menjemputnya di penghujung usia. Warna dunia telah ia habiskan untuk menghiasi masa mudanya. Hingga ia mengabaikan, bahwa ada usia senja yang masih menantinya dibelakang hari.
Mata sipitnya hanya mampu menatap satu wajah kali ini. Melani. Putri bungsunya yang masih bersedia merawat walau dengan separuh hati. Bagaimana tidak? Melani belum juga menikah diusianya yang 30 tahun ini. Masa mudanya habis untuk menunggui Ijah yang terbaring lemah dengan penyakit yang menggerogoti. Entah sudah berapa tahun, tak ada perubahan. Bagaimana ada perubahan, toh tak ada yang bersedia membawa Ijah ke rumah sakit walau hanya sekadar bertemu dokter atau mendapat resep obat. Kelima anaknya entahlah ke mana. Sibuk merantau menjejaki kehidupan masing-masing yang penuh derita. Jangankan peduli keadaan Ijah, untuk makan sendiri pun susahnya minta ampun.
Sepanjang hari, mereka hanya berdua dalam gubuk kecil yang hampir roboh itu. Kayunya mulai rapuh karena terlalu sering terendam air banjir yang datang dari sungai seberang. Tak ada yang menghampiri meski gubuk mereka tak jauh dari pemukiman warga. Mungkin hanya sekadar menjenguk Ijah. Tidak!! Kabar kembalinya Ijah ke kampung ini sudah menjadi berita klasik bagi mereka. Apalagi dengan kondisi Ijah yang saat ini sangat memprihatinkan. Justru menjadi bahan cibiran dari satu mulut ke mulut yang lain. Menyebar dengan cepat terbawa angin ke kampung sebelah.
Matahari masih baik. Menyorot hangat tubuhnya yang terbujur lemah berselimut sarung dari balik cela-cela kecil dinding bambunya. Matanya masih terpejam. Serasa tak kuasa lagi menahan rasa sakit pada kakinya yang semakin hari kian membusuk. Ulat-ulat mulai keluar dari kulitnya yang berubah warna hitam itu. Luka yang pada awalnya hanya seujung jari akibat terjatuh dari tangga, kini merambat hingga selutut. Dan yang lebih parahnya, tak pernah sekalipun Ijah menginjakkan kakinya ke rumah sakit untuk berobat. Maklum, siapa yang peduli? Keberadaannya sama saja dengan ketiadaannya di kampung itu. Warga telah menutup mata padanya. Tak mau ambil pusing dengan kondisinya saat ini. Melani? Melani tak sempat kerja. Bagaimana tidak? Setiap jam, setiap menit, setiap detik mulut Ijah tak pernah bosan memanggil nama Melani.
Ijah perlahan membuka mata. Ternyata kedua matanya masih bisa menangkap sinar mentari yang menyambutnya dengan hangat. Ijah berpikir ia akan tidur panjang untuk selamanya. Matanya akan selamanya terpejam tak terbuka lagi. Ia bosan, letih, menghabiskan sisa hidup di atas ranjang seperti ini. Ia jenuh menatap atap-atap gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan mulai keropos itu. Mungkin menunggu beberapa waktu, rumah itu akan ambrol terkubur bersama tanah. Sayangnya, sikap Ijah tak pernah berubah. Ijah tak pernah menyadari sebuah pelajaran besar dibalik kondisinya saat ini. Justru ia tak henti merintih dan mengeluh tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore. Gubuk kecil itu ramai oleh suara rintihan Ijah.
“Melani, mengapa tak ada orang yang menjenguk ibu?” Rintihnya dengan nada yang lemah.
“Itu semua gara-gara perbuatan ibu sendiri” jawab Melani jutek.
“Ibu salah apa Melani? Ibu tak pernah punya masalah dengan mereka Mel. Mereka saja yang membenci ibu, iri karena mereka tak pernah bisa sejaya ibu dahulu. Karena rasa iri itu, mereka tak suka jika ibu kembali ke kampung ini? Padahal apa salahnya? Ini juga kampung kelahiran ibu” bantah Ijah yang masih saja sempat membela diri. Tak sadar dengan semua yang telah diperbuatnya. Masih saja ia merasa benar walau kini semua yang dulu ia banggakan musnah tanpa sisa.
Tentu saja, jawaban Ijah mengundang emosi Melani. Melani yang tiap hari merawatnya dengan hati separuh tak ikhlas itu, harus betah dan memasang telinga tebal-tebal untuk menghadapi hujaman rintihan Ijah. Siapa yang tidak jengkel? Orang seperti Ijah memang tak patut untuk dikasihani. Dengan keadaannya seperti itu, masih saja ia sempat mengumpat orang lain.
“Ibu, kenapa sih ibu tidak pernah sadar. Dengan enteng ibu mengatakan salah apa? Jadi selama ini ibu tidak pernah sadar jika ibu telah melakukan banyak sekali kesalahan pada warga kampung dan semua anak-anak ibu? Aku masih memandnag ibu, sebagai orang mulia yang telah melahirkanku walaupun ibu tak pernah bersedia mengurus aku dari sejak kecil. Ibu mentelantarkan kami, semua anak-anak ibu begitu saja di kampung ini. Diasuhkan kepada tetangga. Sedang ibu di sana umbar kekayaan besar-besaran” bentak Melani yang tak kuasa lagi menahan emosinya yang ia tahan bertahun-tahun.
“Ibu melakukan semua itu demi kamu semua. Tapi, sekarang apa? Semua anak-anak ibu durhaka tak ada yang peduli dengan keadaan ibu. Apa kamu juga mau durhaka seperti yang lain?” Ijah tetap saja ngotot. Tak mau salah. Tak mau kalah.
Sontak Melani beranjak berdiri. Emosinya memuncak. Perasaannya sempurna terbakar oleh emosi. Geram, kesal, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Bisa-bisanya Ijah mengatakan seperti itu. Ia yang telah puas merasakan segala kenikmatan dunia. Sedang Melani, sama sekali tak mencicipinya sedikitpun sejak ia berusia dini. Dan kali ini ditambah dengan menanggung penderitaan Ijah yang dulu tak pernah secuil pun mengingat anak-anaknya.
“Astaga Ibu!!! Kami semua tidak akan seperti ini jika tidak dari sikap orangtua yang tak becus dalam mendidik anak. Jangan salahkan anak ibu yang saat ini harus meninggalkan ibu karena harus menanggung penderitaan hidup, akibat dari ibu yang sama sekali tak pernah peduli pada kehidupan anak. Ibu kaya raya. Tapi kami? Tak jauh seperti seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan. Ibu tak pernah peduli bahwa kami hanya mampu menetes air mata saat perut kami tak kuasa menahan lapar. Kami harus buta huruf dan bodoh sepanjang hidup karena tak pernah sedikitpun ibu memberi makan pendidikan pada kami. Mana tanggung jawab ibu?” Air mata itu mengalir seketika. Air mata yang selama ini harus terbendung dan jatuh secara sembunyi-sembunyi agar tak terlihat oleh Ijah. Kini terpaksa air mata itu tumpah sebagai saksi penderitaan yang dialaminya selama ini. Segera ia tinggalkan Ijah yang terbaring lemah dengan diliputi rasa keras kepalanya itu. Tetap saja, Ijah tak pernah sadar. Ia tak mencerna sama sekali kata-kata Melani. Tak mengerti bagaimana perasaan Melani saat itu.
“Justru mana tanggung jawab kamu dan kakak-kakakmu sebagai seorang anak, Melani?”
Siapa yang tak mengenal Sutijah? Seluruh pelosok kampung mengenal nama itu. Sebuah nama yang pernah melambung menembus tayangan di berbagai media. Terutama televisi. Mantan istri seorang pengusaha tekstil yang beberapa tahun silam sempat menggemparkan negeri ini. Peristiwa yang tak pernah terlupakan dalam sejarah hidup Sutijah sebagai orang kampung yang sukses merintis bisnis di ibu kota. Tapi, sayang seribu sayang. Tak ada yang membanggakan kesuksesan Sutijah. Sikap Ijah berubah drastis ketika ia memutuskan untuk merantau ke ibu kota sepeninggalkan suami pertamanya. Menitipkan keenam anak-anaknya pada tetangga. Hingga beberapa tahun tak kembali, tak sekalipun mengirimkan kabar untuk anak-anak tercinta. Mengirimkan uang untuk anak-anaknya. Tidak!! Ia lupa semua itu! Ia malu jika ia mengaku bahwa dirinya telah berkepala enam kepada pengusaha itu, sedang dirinya masih cantik jelita layaknya kembang desa.
Tak cukup itu! Ijah bahkan berpura-pura buta saat berpapasan dengan orang sekampung yang juga merantau ke ibu kota seperti dirinya. Tidak melayani mereka yang meminta bantuan untuk masuk pada perusahaan tekstil milik sang suami. Ijah benar-benar telah menjadi kacang lupa kulitnya.
Tapi, Ijah. Tetap saja keras kepala. Membangga-banggakan statusnya yang kini telah lenyap tercabut kesombongannya sendiri. Tak malu ketika ia kembali menginjakkan kaki di kampung itu. Justru merasa bangga ketika semua mata melirik tak suka padanya. Iri pertanda tak mampu. Itulah prinsipnya.
Buat apa ia kembali jika hanya sebagai pelampiasan ketika seluruh kekayaannya ludes habis akibat peristiwa kebakaran hebat yang menimpa perusahaan suaminya itu. Lenyap sudah semuanya. Bahkan sang suami menjadi salah satu korban dalam peristiwa itu. Semua asuransi yang diterimanya habis untuk melunasi hutang-hutang perusahaan yang menumpuk. Tak cukup itu, terpaksa pula ia harus menjual sertifikat rumah milik sang suami sebagai tambahan melunasi hutang.
Kesombongannya telah merebut semua yang berada dalam genggamannya. Menyulut bagai api yang dengat cepat melahap kayu tanpa sisa. Namun, rupanya peringatan Tuhan tak juga memusnahkan watak buruknya itu. Hingga pada akhirnya Tuhan idapkan penyakit gula dengan kadar yang sangat tinggi. Menggerogoti tubuhnya yang telah rapuh karena usia.
Entah apa jadinya Ijah, jika dia selamanya akan seperti itu. Kelima anaknya sudah pergi jauh entah kemana. Tak pernah terlihat batang hidungnya. Tak pernah ada yang memberi kabar tentang anak-anak Ijah yang merantau jauh meninggalkan dirinya. Sekali lagi, siapa yang peduli? ditambah sekarang, Keadaan Ijah semakin memburuk. Kakinya sempurna membusuk hingga paha. Melani hanya melapangkan dada mengurus sang ibu yang berkepala batu itu. Telinganya ia bungkam rapat-rapat meski celoteh sang ibu keluar masuk tanpa bosan. Ia rendam emosinya meski celoteh sang ibu tak sekali dua kali meluapkan amarahnya. Ia letih menanggapi. Toh, untaian seribu nasehat tak pernah sedikitpun melekat dalam hatinya. Selalu ada bantahan yang mengiringi.
Entah sampai kapan hidup Melani datar tak berliku seperti ini. Datar diatas penderitaan berkepanjangan yang tak menemui ujung penyelesaian. Hanya maut jalan satu-satunya tuk melepas penderitaan ini. Tapi kapan? Entah bolehkah ia mengharap agar malaikat segera menjemput nyawa sang ibu. Tak pernah ada senyum sedikitpun yang menggurat di wajah cantik yang tertutup oleh kemurungan beberapa tahun lamanya. Senyum walau sekadar merasakan setitik rasa kebahagiaan. Hingga wajah cantik itu pudar terlampau usia. Suram oleh derita hidup yang tengah menimpa dirinya. Tak ada rona yang berubah dari wajahnya selain titik air mata. Hatinya sepanjang hari dirundung pilu. Letih menunggu sang ibu yang terbaring lemah tak berdaya dengan sejuta celotehan yang memecah keheningan gubuk kecil. Raut kesombongan yang tak pernah sirna dari wajah sang ibu yang sudah terlarut bersama usia. Ia letih menunggu seorang pangeran yang menjemput dirinya. Seorang pangeran yang akan membawanya lari dari penderitaan hidup. Seorang pangeran yang akan melukiskan senyum abadi tanpa mengenal waktu. Namun, kenyataan pahit justru semakin menghantui. Tak perlu dinanti, toh sudah berapa kali seorang laki-laki meminangnya dan mendapat perlakuan sama. Ditolak mentah-mentah oleh sang ibu. Melani sungguh bingung, hatinya berkecamuk. Apa yang harus ia akui dari suara hati kecilnya? Haruskah ia membenci sang ibu yang juga telah merenggut kebahagiaan masa mudanya? Haruskah ia tetap menunggu sang ibu yang tak pernah mengakui belas kasihnya?
Semilir angin berhembus lembut menemaninya yang tengah merenung malam itu. Mencoba membawa penderitaannya yang tertimbun bertahun-tahun hingga membusuk dalam pikiran mudanya. Namun, derita itu telah mendarah daging sejak dirinya terlahir didunia ini. Derita itu memusnahkan kebahagiaan yang harusnya ia renggut semasa hidupnya. Hingga kini, ia kembali tertimpa derita sang ibu di penghujung usia. Ingin rasanya ia menjerit. Segera berlari mencari serpihan kebahagiaannya sendiri.
Hari-hari membosankan. Dengan pemandangan pepohonan tinggi yang dari hari ke hari kian menjulang menembus langit. Batang dan akarnya yang semakin kuat mengakar ke dasar bumi. Dan pada akhirnya mereka juga akan rapuh termakan usia. Gubuk kecil itu, tak jauh pula. Bambu-bambu dan tiang-tiang gubuk yang semakin hari kian keropos, tak kuasa lagi menjadi penyangga. Usia Ijah yang menjemput senja semakin jauh. Tubuhnya yang kini semakin kurus. Kian renta. Namun, tak sedikitpun mengurangi rintihannya. Keluhannya berdengung diantara atap-atap gubuk kecil yang rapuh. Menghuni disana tanpa mengenal waktu. Mungkin mereka juga bosan mendengar rintihan Ijah. Mereka yang telah rapuh, ingin saja menimpali tubuh Ijah yang mendekati maut itu. Biar saja sekalipun tertimbun bersama tanah agar tak terdengar lagi suara-suara bising Ijah.
Baca Juga : Perawan Ku Diambil Adiku Sendiri Saat Aku Tidur
“Melani… Dasar anak tuli! Dipanggil orangtua sedari tadi tak dihiraukan. Melani… uhuk-uhuk” Ijah batuk-batuk. Tenggorokannya telah kering karena raungannya terabaikan.
“Melani.. Uhuk-uhuk” Ijah kembali terbatuk. Mengulang nama yang sama untuk kesekian kali. Dan baru yang terakhir ini, rintihannya tertangkap oleh telinga Melani. Melani berjalan terseok-seok menyeret tanah. Dengan wajah malas, ia melangkah menuju pembaringan sang ibu yang menyedihkan itu. Entah ke mana telinganya ia bawa sedari tadi. Hingga raungan sang ibu terhempas bersama angin. Tak menyelinap sedikitpun atau bahkan sekadar lewat ke dalam telinganya. Perasaan dongkol membanjiri hatinya ketika tubuhnya kembali ia hadapkan pada sang ibu. Wajah tak menyenangkan yang selalu ia jumpa setiap waktu. Mungkinkah Melani membenci sang ibu akibat tingkah lakunya yang membuat dirinya tak pernah merengkuh kebahagiaan hingga diusia sedewasa ini?
“Kamu ke mana saja sih!! Sudah tuli kali kamu! Terlalu sering mengabaikan perintah orangtua!” Bentak Ijah yang masih sempat saja berbicara kasar dengan kondisinya seperti ini.
Entah keberapa kali Melani mendapat perlakuan seperti ini. Kasih sayang dan belas kasihnya selama ini tak pernah sedikitpun menyentuh dalam hati sang ibu. Segala penderitaan yang menimpa hidupnya tak pernah sekilas pun terenungkan oleh sang ibu. Dan entah kesekian kali embun dari matanya mengalir tanpa ada yang menengadah. Jeritan hati yang hanya terdengar oleh alam dan burung-burung yang hinggap di ranting pohon. Segudang pertanyaan yang masih terpendam dan membekas hitam hingga menimbulkan sebuah noda yang tak pernah mampu hilang sepanjang hidupnya. Sebuah pertanyaan yang tersimpan lama. Dan ternyata, hanya mendapat sebuah jawaban yang semakin menusuk hati. Dari sana, timbul perasaan benci yang sesungguhnya terlarang untuk dirinya. Namun, mungkinkah Tuhan mengizinkan?
“Kamu sekarang sudah mulai durhaka sama orangtua. Iya Melani?? Ibu tahu kamu tak pernah ikhlas merawat ibu! Ibu tahu kamu masih jengkel dengan ibu gara-gara semua lelaki yang meminang kamu tertolak! Ibu juga tahu kalau kamu ingin menikah, hidup bahagia bersama suami kamu agar terlepas dari tanggung jawab kamu merawat ibu yang menderita!”
“Jika memang seperti itu, pergi saja sana kamu bersama kakak-kakakmu yang tak menengok keadaan ibu yang sekarat seperti ini! Kamu dan kakak-kakakmu memang sama! Tak pernah menghargai pengorbanan ibu yang mencari nafkah untuk kebahagiaan kalian!”
Lama ia diam, namun, kata-kata Ijah semakin menjadi. Menyulut amarah yang sedari tadi berusaha tersiram dengan air kesabaran. Namun, mulut Ijah tak pernah henti berceloteh bagai burung merpati yang hinggap di jendela setiap pagi. Bersiul ramai menyambut mentari. Kata-kata Ijah tak pernah menemukan sebuah titik pemberhentian hingga sang lawan bicara meninggalkannya sendiri.
“Ibu, jika aku memang durhaka. Aku sudah dari dulu meninggalkan ibu sendirian di sini. Aku juga ingin bahagia bu? Aku mohon agar ibu mengizinkan aku untuk bahagia dengan caraku sendiri. Aku juga ingin menikah seperti wanita pada umumnya. Tapi kenapa ibu tak pernah memberikan izin itu selama hidupku! Ibu justru menimpaliku dengan derita yang berkepanjangan. Ibu bebas bahagia ketika kami semua anak-anak ibu berada dalam lilitan derita. Bagaimana ibu bisa mengingat kami saat itu?” Air mata Melani sempurna mengalir deras. Tak kuasa menahan semua beban penderitaan hidup. Tak kuasa menghadapi kerasnya watak sang ibu yang kunjung menjemput kesadaran dan penyesalan atas semua yang telah diperbuat. Kini dirinya yang menjadi korban sekaligus pelampiasan.
Percuma saja berbicara dengan Ijah. Toh, setiap bantahan Melani tak pernah sedikitpun menyelinap ke dalam pikirannya. Wataknya terlalu keras hingga tak ada satu orang pun yang bisa memecah kekerasannya. Mengalahkan batu yang bisa berlubang karena tertetes oleh air dalam waktu panjang. Namun, Ijah? Derita seberat ini tak mampu mengusir otak buruknya itu.
Langit yang gelap mencekam. Serasa menghalangi sorot sinar rembulan yang mencoba menerangi gubuk kecil itu. Pepohonan tinggi yang tak terlihat lagi hijau daun segarnya. Semilir angin yang berhembus kencang. Semakin kencang. Menyusul badai yang menerpa langit kampung malam itu. Cahaya lilin dalam gubuk kecil itu mulai kabur tertiup angin. Bersamaan dengan itu, diam-diam Melani merapikan semua pakaiannya ke dalam kerudung lebar yang ia jadikan tas gendong. Lalu menyelinap keluar dengan tetesan air mata yang tak terhenti mengalir. Serasa tak rela jika dirinya meninggalkan sosok yang tengah terbaring lemah di atas ranjang itu. Namun, semua belas kasihannya telah tertutup oleh awan kebencian yang menyeruak dan menggelapkan pikirannya. Malam itu, ia melangkah pasti. Menerobos kegelapan malam. Entah ke mana. Yang pasti ia akan menyusul kakak-kakaknya. Mengais kebahagiaan yang belum pernah ia temukan selama ini. Ia tinggalkan tubuh yang semakin hari kian kurus kering itu.
Badai semakin besar menerjang. Gubuk kecil itu, entahlah. Semua mengira akan habis riwayatnya malam ini. Benar saja. Gubuk yang kayu penyangganya telah keropos itu tak kuasa lagi menopang. Tak kuasa lagi bertahan sedang badai bertiup besar memaksanya untuk ambruk. Sedang tubuh Ijah semakin menggigil. Mulutnya kembali meraung-raung nama Melani. Namun sayang seribu sayang, sang pemilik nama tak lagi menghuni gubuk kecil. Pergi tuk meninggalkan derita yang telah ia timpakan padanya. Tak kuasa menahan dinginnya angin malam yang berhembus, nafasnya Ijah tersengal-sengal. Serasa maut telah menjemputnya dan telah sampai di ambang tenggorokan. Bersamaan dengan robohnya gubuk itu, nyawa Ijah telah melayang ke atas langit. Tamatlah riwayatnya. Namun, sejarah masih mengenang. Sebagai sample manusia-manusia yang lupa akan asalnya.
|
















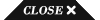













No comments:
Post a Comment